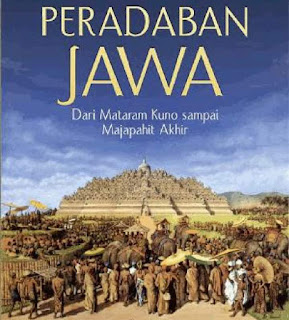Brawijaya Goa Bribin - Pantai Ngobaran - Tan Keno Kinoyo Ngopo -
Pada permulaan masa dewa-dewa, keberadaan lahir dari ketiadaan. (Rig Veda).
Suatu waktu di sekitar akhir abad XVI, seorang ‘Raja Jawa’ manekung di sebuah gua. Menyendiri. Meninggalkan riuh kekuasaan yang ‘ambruk’. Melenguhkan penderitaan Jawa. Seakan hendak merelakan kebesaran ‘agama’nya dipergantikan; nuju kelepasan. Kemudian, ia mengulang-ulang pertanyaan ini: akan memilih ke mana tubuh-ruhku, ke agamaku ataukah ke ‘anakku’?
Barangkali, jauh di kedalaman hatinya, sebelum menepi-menyepi ke Gua Bribin itu, sebelum meninggi di tebing Ngobaran, sebelum memelosok di gunung-gunung Gunungkidul, ia sudah punya jawaban. Jawaban setua paganisme Jawa. Bukankah Jawa telah cukup dari mula; tak butuh tetek-bengek lagi ideologi? Bukankah orang-orang dunia kuno [baca: Yunani kuno] menyebut Jawa tempat leluhurnya menancapkan paku sebagai ‘tanah suci’, white island; the land pured by fire?
Hanya tampak bersit cahaya dari luaran, untuk beberapa waktu ia merenungkannya. Toh pada akhirnya, ia, raja Majapahit yang ‘ada’ dalam angan-angan kolektif rakyat pegunungan selatan, yang tak pernah sama sekali disebut dalam prasasti atau manuskrip sebagai raja terakhir Majapahit―karena sumber prasasti menyebut Raja Majapahit terakhir dari Dinasti Girindrawarddhana, tokoh yang dituturkan ulang kali dalam upacara-upacara, legenda, dan mitologi, yang diceritakan berbeda-beda dalam Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Darmogandul tentang keberadaannya menjelang runtuhnya Majapahit, memilih moksa: senyap yang tanpa bekas.
Rakyat punya versi sejarah sendiri tentangnya. Keyakinannya lebih tertanam pada apa yang telah indah dan akan selalu indah di bumi Jawa, di nusa-antara; Eden yang penuh tetumbuhan. Menumbuhkan biji-biji Ideologi. Islam adalah tetumbuh yang keluar dari tanah pertiwi, dan ia, Brawijaya, satu dari sekian bapak sejarahnya di waktu-waktu kemudian. Setelah mengembara sekian lama akhirnya si biji tumbuh menjadi anak ideologi, pulang pada sang ibu, lantas setelah si anak menemukan si ayah diam di situ, dengan bahasa dekoratif yang tenang ia menginjak bapaknya. Menyetubuhi ibunya.
‘Orang-orang’ menganggap pilihan Brawijaya kontroversial. Dan kontroversi metafor bagi kreatifitas. Namun sudah banyak disebutkan dalam cerita-cerita: Raden Patah pulang membawa oleh-oleh, agama hubb yang akan menentramkan nusantara, merubah ibu pertiwi menjadi ‘madani’. ‘Buku sejarah’ pernah mewartakan, manusia berusaha menciptakan sejarah demi visi kemenangan, kejayaan, keadilan satu ideologi, yang dipercaya sebagai ‘satu-satunya’ jalan bagi kehidupan yang serba terbatas.
Suatu wilayah geografi sebagai ‘pan-islam’ adalah sebuah angan-angan. Dan melalui bahasa, Raden Patah mencoba mewujudkannya. Bahasa berujung ganda. Konon ia, Si Anak, akan ‘mengajak’ ayahandanya ke surga. Dan Si Bapak, tanpa ragu, sebenarnya telah memilih surganya sendiri. Bukankah dalam ‘kitab-kitab’ disebutkan bahwa nusa-antara adalah surga, di timur? Bukankah Barat mencari ‘ekstator’ di timur, di wilayah yang katanya disepakati bernama (h)indus-nesos ini? Bukankah Gunung kidul surga bagi manusia pra-aksara? Bukankah sejak 1800-an pegunungan seribu oleh Junghuhn disebut sebagai ‘taman Firdaus’? Brawijaya tak perlu sorga, karena ia di sorga, ia sorga.
Cerita moksa sang raja bermula dari alur yang tidak lah njlimet: Raden Patah bukan ‘orang Jawa’, ia tokoh’ dalam sejarah Jawa. Ini tentang ‘anak’ yang mencari bapaknya; ngawu-awu sudarma jika meminjam terma pewayangan. Ia anak ”Elit Arab” yang karena determinasi peperangan lantas di-aku-kan sebagai anak oleh Brawijaya. Dan, lagi-lagi, konstruksi sejarah nusa-antara yang terpaut langsung atau tak langsung dengan hadirnya ‘Islam’ tetaplah abu-abu, bahkan seluruh bangun sejarah nusa-antara yang ‘kewolak-walik’. Sang Anak tak merasa sebagai bagian klan pribumi yang ‘kafir’; sebutan bagi orang-orang yang kediriannya tak dibentuk oleh baju ”Islam”; oleh langit Islam. Sang Bapak bukan ”Islam”. Dengan ‘kepercayaan Arab’ yang dihaluskan dalam Kitab ia dianggap nista, melenceng, tak pantas. Sang Anak hendak menuntut tahta, sekaligus menegakkan ‘a-gama’ yang ia bawa dari rantau. Sang Bapak memilih senyap.
Membaca moksa Brawijaya seakan meletakkan Complex Oedius psiko-analisisnya Freudian di lembar-lembar tanah Jawa. Teringat sebuah ketegangan antara Sangkuriang dan ayahnya, atau antara Watugunung dengan para dewa. Jika Oedipus membunuh Laius lantas mendapatkan Jocasta beserta kerajaannya, maka Sangkuriang membunuh ayahnya (anjing Si Tumang) dan kemudian hari mengawini Dayang Sumbi, Watugunung mengawini Shinta, ibunya, maka Raden Patah ‘yang Islam’ menyingkirkan ‘ayahnya’ untuk saresmi dengan Pertiwi, lantas menjadi raja Jawa.
Raden Patah resah layaknya remaja yang sedang mencari kediriannya yang terbelah, risau akan identitas. Siapa aku? Barangkali di dalam hatinya ia berkata: Aku adalah putra raja Jawa! Aku membawa agama perdamaian! Aku bukan anak haram! Aku pemimpin baru, harapan baru! Kelahiran baru! Namun, pantaskah seorang anak menyingkirkan bapak demi sebuah konsep kemaslahatan? Bukankah perkawinan sumbang melahirkan bencana?
Dulu, di masa yang lebih tua, seseorang dari tanah seberang dengan genealogi ‘ibrahiman’ menuju tanah Jawa, mengawini putri leluhur Jawa bernama Aki Tirem dan menggantikannya menjadi raja. Kratonnya bernama Salaka-Nagara [Negeri Perak]. Ia mewartakan ide ‘tuhan yang menyatukan’: allahu ahad. Kemudian, di masa-masa yang kemudian, anak cucu Jawa mengamini ide ketuhanan ini; menggunakannya sebagai laku kehidupannya. Ia seperti Bathara Brahma yang mengabarkan ‘ketuhanan’ di tanah Jawa. Tuhan yang menyatukan. Cerita ini seperti ide tentang tuhan yang mengembara, kemudian di waktu-waktu berikutnya ide tentang tuhan itu pulang kampung.
Terkadang konsep ”tuhan” hanya dilihat sebagai salah satu terma leksikal: theos saja. Ia tak dipersejajarkan dengan konsep ‘paling mutakhir’ dari ‘bukan konsep tuhan’ yang lain. Dengan demikian, tentu saja, kemaslahatan Raden Patah dengan Allah Semitik-nya seakan-akan ‘antagonisme’ bagi Brawijaya. Bersama dengan itu, Brawijaya tak dianggap punya daya khalifah yang universal. Ia bukan khalifah, namun Brahmin. Dan barangkali Brawijaya waktu itu menjawab: “Jawa adalah Islam, namun ‘Islam’ terkadang bukan Jawa, Anakku!” Dan ia pun tampak tak berkenan dengan ekspresi-agresif Raden Patah dan Sunan Kalijaga yang penuh determinasi atas nama ‘Islam’. Mereka ‘memburu’ Brawijaya dari Ngawen, Nglipar, Gubug Gedhe, Ngobaran, hingga Bribin, dalam rangka agar ‘menjadi Islam’.
Bukankah ia sudah Islam, dengan baju Budo? Bukankah ia tak pernah memamerkan kepintaran ‘kitab’ dengan suara-suara yang hebat? Brawijaya tidak dengan ‘sholat’ untuk menuju ‘cahaya maha cayaha’, untuk menjadi ‘cahaya’. Ia cahaya. Ketika beberapa helai rambut gondrongnya ditebas dengan pisau, sebagai kode ‘pengislaman’, ia moksa. Ia lenyap; tubuh, pikir, jiwa, dan ruhnya. Kini ia mungkret, karena selama ruang waktu ini keyakinan telah membuatnya mulur. Ia bintang yang tak lagi punya massa. Ia supernova. Ia pekat. Ia memangsa tubuhnya sendiri. Ia irasional. Ia monisme. Dan tentu saja, lagi-lagi, segala aroma Monistik-Timur yang ‘irasional’ Platonik dianggap berbahaya seperti oleh Pythagoras, karena akan merusak alam semesta.
Dari cerita-cerita yang laten di seluas gunung-gunung selatan, Brawijaya menawarkan sesuatu yang akan selalu hidup sebagai spirit paganisme: Jawa adalah heningnya laku, di goa-goa, bukan teriakan yang menggemuruh.
(Untuk Naskah Darmogandul menurut profesor Agus Sanyoto dibikin Belanda untuk memecah belah)